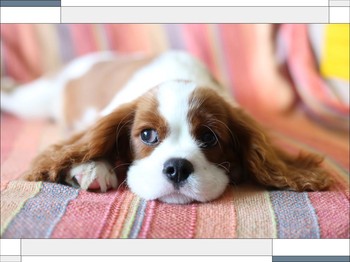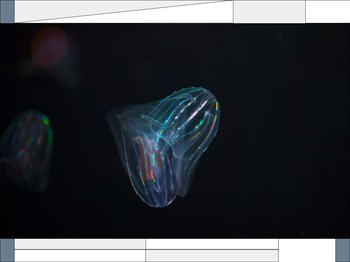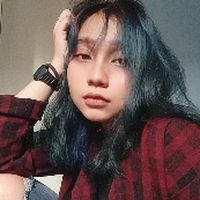University of Oxford dikenal sebagai salah satu universitas peringkat nomor satu di dunia sekaligus universitas tertua. Pengaruhnya pun tak main-main dalam bidang akademik maupun penelitian global.
Namun, beberapa hari belakangan ini, media sosial X hingga Instagram Oxford penuh dengan kritikan pedas dari netizen Indonesia. Bukan hanya masyarakat umum, kalangan akademisi, peneliti, bahkan tokoh pendidikan Indonesia seperti Anies Baswedan ikut memberikan kritik kepada University of Oxford.
Lantas, apa yang membuat netizen Indonesia begitu marah di media sosial universitas terkemuka di dunia ini?
Unggahan Kontroversial Oxford dalam Penemuan Terbaru
Beberapa waktu lalu, bungka bangkai atau Rafflesia berjenis langka, Rafflesia hasseltii, baru saja ditemukan oleh sekelompok peneliti dari University of Oxford, BRIN, Kebun Raya Bogor, Universitas Bengkulu, Universitas Filipina Los Banos, dan Lembaga Kehutanan Malaysia di Kawasan hutan Hiring Batang Sumi, Nagari Sumpur Kudus, Sumatera Barat.
Penemuan itu diabadikan oleh sebuah video yang diambil oleh salah satu peneliti, Dr. Chris Thorogood yang memperlihatkan bunga Rafflesia hasseltii yang sedang mekar dan peneliti lainnya yang menangis melihat bunga tersebut. Thorogood pun membagikan video tersebut dalam akun X miliknya dan mendapatkan sambutan dan dukungan dari pecinta flora.
Namun, dari situlah masalah muncul. Ketika University of Oxford mengunggah sebuah siaran pers lewat akun media sosialnya yang menuliskan tentang perjalanan ilmuwannya yang menembus hutan dan melewati habitat harimau untuk menemukan bunga tersebut. Namun, sayangnya dalam unggahan tersebut, Oxford sama sekali tidak menyebutkan para peneliti dari Asia Tenggara termasuk Indonesia yang ikut andil dalam penemuan bersejarah ini.
Siaran pers dengan judul An international group of scientists, including botanists at the University of Oxford's Botanic Garden, has issued an urgent call ini, memicu kontroversi karena hanya menyebut Oxford di dalamnya, sementara ilmuwan Asia Tenggara hanya disebutkan 'kelompok ilmuwan internasional'.
Meskipun artikel ilmiah yang menjadi dasar laporan berita ini dengan jelas menunjukkan bahwa penelitian tersebut dipimpin dan dilakukan terutama oleh para ilmuwan dari Filipina, Indonesia, dan Malaysia, teks publik Oxford menampilkan Chris Thorogood sebagai juru bicara utama dan tokoh yang memegang otoritas ilmiah dalam narasinya.
Ini diperkuat dengan unggahan video mereka di akun Instagram mereka yang menyebut Thorogood saja, tanpa penyebut Septian Andriki, ahli botani lapangan Indonesia yang memetakan situs, membimbing tim, dan menghabiskan lebih dari satu dekade mencari spesies ini.
Lagi-lagi, Thorogood kembali muncul sebagai narator utama, menafsirkan makna ilmiah dari peristiwa tersebut, sementara Septian Andriki hanya ditampilkan sebagai anggota tim tanpa identitas yang jelas. Setelah mendapatkan kritik, unggahan itu pun diedit oleh pihak Oxford.
Namun kandung sayang, unggahan sebelumnya telah diadaptasi oleh berbagai media internasional yang hampir sama. Misalnya artikel The New York Post, menuliskan judul artikel Flower hunter Septi Deki Andrikithat was seen sobbing with joy. Ini menunjukkan ahli botani Indonesia hanya figur sampingan, padahal ahli Indonesia juga sama pentingnya dengan ahli dari Oxford tersebut.
Akibatnya, kritikan demi kritikan pun muncul kepada University of Oxford. Para kritikus pun menyebutnya dengan penelitian parasut.
Kolonialisme Akademik
Dikutip Science Watch Dog, sebuah unggahan neohistorian.id menyoroti betapa praktik yang menyerupai 'sains parasut' ini mencoba melanggengkan hierarki lama bahwa peneliti 'barat' adalah intelektual utama, sementara peneliti 'Asia' hanyalah tenaga bantuan. Padahal keduanya adalah aktor yang memiliki tugas serupa.
Mungkin penyertaan nama dalam sebuah penemuan tampak biasa saja bagi orang awam. Namun bagi sejarah penelitian Indonesia hal ini tentu saja sangat penting. Melihat framing Oxford terlihat meminimalisir identitas ilmiah lembaga-lembaga Asia Tenggara, akhirnya menciptakan ketidakseimbangan struktural yang berulang.
Konservasi Rafflesia bersifat kolaboratif. Konservasi ini dibangun berdasarkan pengetahuan para ilmuwan Asia Tenggara, pemantau komunitas, kelompok ekowisata, dan pelaku kehutanan yang melindungi habitat sepanjang tahun. Penemuan kembali ini merupakan peristiwa ilmiah, tetapi juga merupakan momen sosial dan politik.
Siapa yang berbicara pada momen tersebut membentuk siapa yang diakui sebagai otoritas ilmiah dan siapa yang diakui sebagai penjaga salah satu bunga paling luar biasa di planet ini. Apalagi secara jangkauan 'suara', Oxford lebih punya power mengambil telinga-telinga global.
Kerangka BRIN mungkin tidak memiliki skala yang sama, tetapi menawarkan koreksi yang didasarkan pada konteks nasional. Seiring berlanjutnya perdebatan tentang "penelitian parasut", kasus Rafflesia menggambarkan bagaimana pilihan komunikasi dapat memperkuat hierarki lama atau menciptakan ruang bagi representasi ilmu keanekaragaman hayati global yang lebih akurat dan adil.
Kalau konservasi itu ingin menjangkau global, narasisnya tentu saja harus jujur dan menjangkau keseluruhan kegiatan yang terjadi di lapangan. Bukan cuma mengandalkan 'nama besar' institusi.
(DIR/DIR)