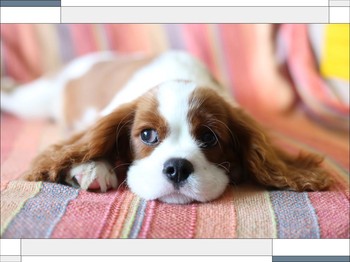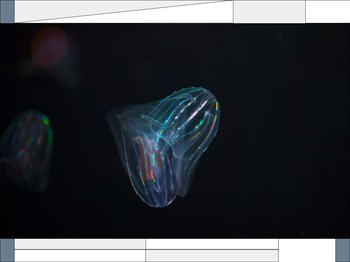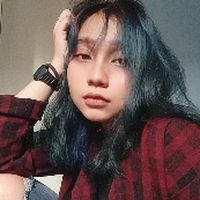Banyak yang beranggapan, riset, penemuan, hingga inovasi yang dilakukan oleh peneliti Indonesia sangat jauh tertinggal dari negara tetangga. Bahkan profesi seorang peneliti tidak lagi menjadi sesuatu yang prestise bagi anak-anak muda Indonesia alias 'tak ada uangnya'.
Padahal menjadi peneliti di luar negeri, bisa digaji puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan hanya dengan satu penemuan yang bisa mengubah suatu negara. Sedangkan di Indonesia, peneliti bak seorang pengangguran, saking riset dan inovasinya 'tak laku'.
Faktanya, Indonesia tidak pernah kekurangan talenta dan ide-ide cemerlang. Mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia kerap mengikuti ajang inovasi internasional untuk unjuk gigi bahwa Indonesia juga punya bakat dalam bidang sains dan teknologi. Namun inovasi itu hanya segelinting yang menuju puncak, sisanya terbengkalai di laboratorium yang kini dikenal sebagai jurang maut inovasi.
Dikutip The Conversation, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki hampir 600 paten. Tapi cuma 10 paten yang pernah dilisensikan dan digunakan di industri dalam negeri. Lantas, mengapa ide-ide brilian para peneliti kita hanya berakhir di balik pintu laboratorium?
Penyebab Inovasi dan Paten Tak Terlihat
Ada banyak penyebab inovasi kita selalu kandas sebelum sampai pasar. Mulai dari kebijakan riset yang tak konsisten, regulasi sering berubah, politik anggaran, rendahnya komitmen industri menjadi offtaker riset dan kampus yang terjebak dalam logika publikasi.
Pemerintah sebenarnya mencoba menjembatani jurang maut ini dengan berbagai macam program. Misalnya pada 2021, ada program Matching Fund Kedaireka. Setidaknya ada 427 proposal yang dibiayai pada tahun 2021 dan jumlahnya meningkat menjadi 1.093 proposal di tahun berikutnya.
Pemerintah mengklaim kalau program ini telah mendongkrak skor University-Industry Collaboration _dalam _Global Innovation Index dari 53,5 (2020) menjadi 87,4 (2023). Hasilnya, peringkat Indonesia pada Global Innovation Index melonjak dari 87 (2021) ke 61 (2023).
Ini menunjukkan kalau pemerintah Indonesia masih mengukur keberhasilan dari jumlah proposal dan peringkat indeks global. AKhirnya jumlah proudk yang bertahan di pasar atau memberi manfaat langsung agar mendapat perhatian lebih. Namun dibalik usaha tersebut, banyak yang mengkritik Matching Fund karena masih berhenti di level kolaborasi simbolik saja.
Sebatas berbagi dana riset, seminar bersama, atau pilot project. Tidak ada yang benar-benar menjamin bahwa semua yang dilakukan akan berdampak nyata pada masyarakat. Mitra industri pun hanya hadir di atas kertas demi memenuhi syarat proposal.
Mereka hanya menuliskan kontribusi berbentuk non-uang seperti tenaga, ruang, layanan, dan barang, bukan sebagai seseorang yang menggunakan inovasi tersebut. Sementara itu, universitas kerap menjadikan program ini sebagai 'jalan pintas' untuk menambah portofolio kerjasama dengan industri daripada memilih mengkomersialisasi inovasi tersebut.
Banyak Riset, Tapi Tak Laku di Pasar
Dilansir Antara, anggara riset Indonesia pernah mencapai Rp6,46 triliun pada 2022, dan menanjak pada tahun 2023 menjadi Rp9,38 triliun. Akan tetapi, walaupun dana ini meningkat, dinamika jumlah anggaran riset belum berbanding lurus dengan dampak ekonomi yang dihasilkan.
Kontribusi riset terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 0,31%. Persentase sumbangan ini jauh di bawah Singapura (2,2%) atau Korea Selatan (4,5%). Sementara itu, beban riset 83 persen masih berasal dari kas pemerintah. Industri 9,15 persen, dan universitas 2,65 persen. Jadi, industri di Indonesia hanya mau membeli teknologi asing yang siap pakai, ketimbang berinvestasi ke riset yang dilakukan anak bangsa.
Bila melihat cerita-cerita para inovator di luar negeri, sepertinya semua berjalan mulus. Inovasi-inovasi baru selalu didukung oleh pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Salah satunya adalah tetangga negara kita, Australia yang mengelola relasi universitas dengan industri secara sistematis.
Mereka mengembangkan kurikulum berbasis industri, inkubator bisnis, kantor yang menerjemahkan pengetahuan untuk tujuan komersialisasi, hingga alur yang jelas dari riset dasar hingga komersial. Hasilnya, Australia bisa menciptakan work integrated learning (program yang menghubungkan mahasiswa dengan perusahaan yang sesuai bidangnya) sehingga lulusan perguruan tinggi bisa cepat terserap pasar.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kita sebenarnya sudah mulai mengadopsi pola ini melalui kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang kini bertransformasi menjadi Diktisaintek Berdampak. Data menunjukkan bahwa 1,55 juta mahasiswa telah mengikuti program ini sejak 2019. Mereka mendapatkan pekerjaan 2,4 bulan lebih cepat dengan gaji 1,4 lebih tinggi daripada yang tidak mengikuti program ini.
Ini bukti penting bahwa kurikulum berbasis industri efektif mempersempit jurang inovasi. Hanya, program di Indonesia masih memiliki kelemahan sebab relasi kampus dan industri seringkali sebatas penandatanganan nota kerja sama tanpa tindak lanjut nyata.
Sayangnya sampai saat ini, inovasi yang dilakukan oleh anak bangsa hanya terhenti di kamar laboratorium. Padahal bisa saja, dari inovasi yang diciptakan itu ada 1-3 inovasi yang mampu mengubah Indonesia agar bisa bersaing di sektor sains dan tekonologi dunia.
Sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya membangun sebuah ekosistem yang solid dan terintegrasi sehingga mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi inovasi nyata yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Jadi, kita tak melulu mengandalkan teknologi negara lain.
(DIR/DIR)