Ketika film Arrival (2016) diputar di bioskop, film itu bukan sekadar tontonan fiksi ilmiah biasa. Diangkat dari cerpen karya Ted Chiang berjudul Story of Your Life, film tersebut membawa penonton pada perjalanan menakjubkan tentang bagaimana bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga cara kita memahami dunia termasuk konsep waktu, ruang, dan realitas.
Dalam film tersebut, bahasa alien yang unik mengajarkan sang tokoh utama untuk memandang waktu secara non-linear. Perubahan cara berpikir ini menjadi kunci dalam memahami cerita dan menyelamatkan umat manusia. Konsep ini dikenal sebagai linguistic relativity atau hipotesis Sapir-Whorf, yang menyatakan bahwa bahasa memengaruhi cara kita berpikir dan memahami dunia meskipun penting dicatat bahwa teori ini masih menjadi perdebatan dalam komunitas ilmiah.
Menariknya, jika kita menilik bahasa Indonesia, terdapat potensi luar biasa untuk memahami bagaimana sistem komunikasi ini membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat sehari-hari. Bahasa Indonesia, dengan fleksibilitas dan kekayaan makna ganda, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan bahasa-bahasa seperti Inggris atau Jerman yang cenderung lebih ketat dan spesifik dalam strukturnya.
Bahasa sebagai Lensa Pemikiran
Hipotesis linguistic relativity berargumen bahwa struktur suatu bahasa memengaruhi bagaimana penuturnya memandang dan menafsirkan dunia. Bahasa adalah lebih dari sekadar kata dan tata kalimat; ia berfungsi sebagai lensa yang membingkai persepsi, pemikiran, dan budaya.
Dalam Arrival, bahasa alien menghadirkan tantangan pada pola pikir manusia yang linear dan berorientasi pada waktu sebagai suatu urutan. Tokoh utama belajar untuk melihat masa depan dan masa lalu secara simultan, karena bahasa alien itu memuat konsep waktu yang melingkar dan non-linear.
Walaupun ini fiksi, sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa penutur bahasa dengan struktur gramatikal dan kosakata berbeda memiliki pola pikir yang bervariasi terkait konsep waktu, ruang, dan hubungan sosial. Bahasa Inggris, misalnya, dengan tenses yang jelas membedakan waktu lampau, sekarang, dan masa depan, mendukung pola pikir yang sangat terstruktur dan linear. Sebaliknya, bahasa dengan makna ganda dan tata bahasa yang lebih fleksibel membuka kemungkinan interpretasi yang lebih luas serta pola pikir yang lebih adaptif dan inklusif.
Keunikan Bahasa Indonesia dan Pengaruhnya pada Pola Perilaku
Bahasa Indonesia dikenal kaya akan kata-kata yang bermakna ganda dan struktur kalimat yang relatif lentur. Contohnya, kata "mau" dapat mengandung makna niat, harapan, atau hanya merupakan ungkapan sopan santun. Kata "bisa" tidak hanya menandakan kemampuan, tetapi juga mengekspresikan kemungkinan. Ungkapan "nanti dulu" bisa berarti waktu yang tidak pasti, entah segera atau di waktu yang akan datang.
Selain itu, struktur kalimat bahasa Indonesia memungkinkan pergeseran makna berdasarkan intonasi, konteks, dan budaya komunikasi. Misalnya, kalimat "saya pikir begitu" dapat diartikan yakin, ragu, atau bahkan menolak secara halus-semuanya tergantung pada situasi dan nada pengucapan.
Fenomena ini mencerminkan budaya komunikasi Indonesia yang sangat menghargai keharmonisan, kesopanan, dan kompromi. Pola pikir tersebut terbentuk dan diwariskan lewat bahasa, yang menekankan penghargaan pada konteks dan nuansa, bukan sekadar fakta yang eksplisit.
Bagaimana bahasa memengaruhi perilaku sosial? Di Indonesia, komunikasi cenderung bersifat implisit dan sarat makna tersirat. Hal ini berkaitan erat dengan karakter bahasa Indonesia yang memberikan ruang bagi ambiguitas dan interpretasi beragam.
Dalam budaya ini, kritik sering disampaikan secara halus untuk menghindari perasaan tersinggung. Penolakan biasanya dibungkus dengan kata-kata seperti "mungkin" atau "sepertinya", sedangkan permintaan sering kali disampaikan secara tidak langsung. Fleksibilitas bahasa ini membentuk pola pikir yang toleran dan mengedepankan harmoni sosial, alih-alih konfrontasi terbuka.
Perilaku sehari-hari seperti sikap sopan santun, menghindari konflik langsung, dan menghormati hierarki juga merupakan cerminan bagaimana bahasa membingkai cara kita berinteraksi dan memahami dunia sosial.
Sementara Bahasa Inggris dan Jerman memiliki struktur yang lebih spesifik dan ketat, sehingga menawarkan sedikit ruang untuk ambiguitas. Bahasa Inggris misalnya, sangat bergantung pada tenses yang berbeda untuk menunjukkan waktu kejadian dengan jelas. Bahasa Jerman memiliki gramatika yang kompleks termasuk gender gramatikal, yang memengaruhi pilihan kata dan susunan kalimat.
Kekakuan struktur ini mendorong penuturnya untuk berpikir secara linear dan langsung, terutama dalam memandang konsep waktu, ruang, dan relasi sosial. Hal ini berimplikasi pada pola komunikasi yang lebih eksplisit dan kurang fleksibel dalam menerima makna ganda atau interpretasi yang beragam.
Memahami bagaimana bahasa Indonesia membentuk pola pikir memberi kita alat penting untuk melihat budaya dan perilaku bangsa dari sudut yang berbeda. Ini memiliki relevansi besar dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, komunikasi lintas budaya, hingga pengambilan keputusan dan diplomasi.
Misalnya, dalam dunia pendidikan, pengakuan terhadap sifat fleksibel bahasa Indonesia dapat membantu merancang metode pengajaran yang lebih kreatif dan adaptif. Dalam komunikasi bisnis dan politik, pemahaman ini bisa meningkatkan efektivitas negosiasi dan mempererat hubungan antar pihak.
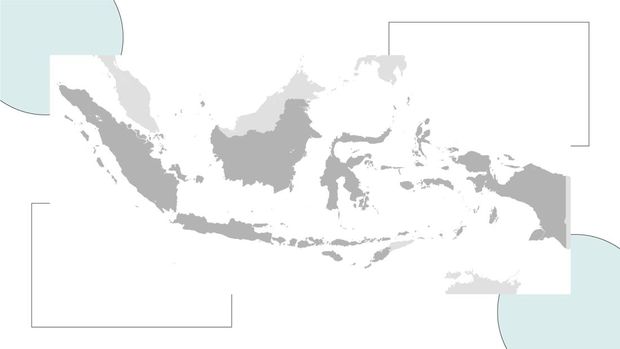 Indonesia/ Foto: Wikimedia Indonesia/ Foto: Wikimedia |
Bahasa Indonesia Sebagai Kunci Pemikiran Bangsa
Di era globalisasi dan digitalisasi, menjaga dan mengembangkan kekayaan bahasa Indonesia sebagai alat berpikir dan berkomunikasi merupakan tugas penting agar bangsa tetap memiliki identitas sekaligus mampu berkompetisi secara cerdas di panggung dunia.
Film Arrival dan cerpen "Story of Your Life" karya Ted Chiang mengajarkan kita satu hal penting: bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan pembentuk dunia tempat kita hidup. Bahasa Indonesia, dengan segala keunikannya, bukan sekadar cara kita berbicara, tetapi juga cermin pola pikir dan perilaku masyarakat.
Menggali bahasa Indonesia lebih dalam berarti memahami bagaimana bangsa ini memandang waktu, ruang, dan hubungan sosial-dan bagaimana hal tersebut membentuk kepribadian kolektifnya. Dengan kesadaran ini, kita dapat merancang komunikasi, pendidikan, dan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai karakter bangsa.
Bahasa Indonesia bukan hanya warisan budaya, tetapi juga kunci masa depan cara kita berpikir dan bertindak di dunia yang terus berubah.
Penulis: Andy Wijaya
*Segala pandangan dan opini yang disampaikan dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi institusi atau pihak media online.*
(ktr/DIR)


