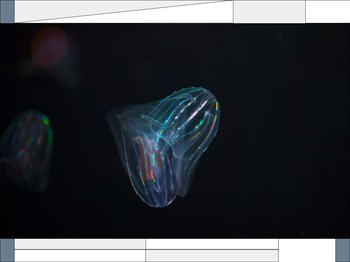Suatu siang, mood saya sedang bagus. Atasan memuji hasil kerja, presentasi untuk klien berjalan lancar, dan seorang teman mengajak makan enak sepulang kantor. Tiba-tiba, kebahagiaan itu hilang, buyar dalam hitungan detik ketika saya membaca laporan tentang suhu global yang menembus rekor tertinggi.
Untuk pertama kalinya, suhu global melampaui 1,5 derajat celsius di atas rata-rata suhu era pra-industri (1850-1900). Angka 1,5°C mungkin terlihat kecil, tapi itulah ambang batas yang disebut sebagai titik kritis oleh para ilmuwan.
Saya melihat foto gunung es mencair, video kebakaran hutan, cerita gagal panen akibat kekeringan ekstrem, dan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Mendadak, saya merasa sesak. Kepala saya ramai oleh pertanyaan-pertanyaan, untuk apa saya bekerja keras kalau dunia perlahan-lahan di ambang kehancuran? Masih adakah masa depan buat anak-cucu saya?
 Ilustrasi bumi yang panas/ Foto: Getty Images Ilustrasi bumi yang panas/ Foto: Getty Images |
Ketakutan pada Bumi yang Makin Memburuk
Barulah beberapa hari kemudian saya paham kondisi itu disebut eco-anxiety, suatu kecemasan yang muncul akibat kondisi bumi yang semakin memburuk. Di seberang samudera, orang-orang juga merasakan hal yang sama. Vashti-Eve Burrows, misalnya, seorang mahasiswi asal Bahama. Setelah Badai Dorian meluluhlantakkan negaranya pada 2019 yang mengakibatkan 50 orang meninggal dunia, ia dicekam rasa cemas yang belum pernah ia rasakan. Dalam kutipan yang dimuat di jurnal Nature, Burrows merangkum seluruh kecemasannya dalam satu pertanyaan: "Apakah Bahama masih ada 20 atau 30 tahun mendatang?"
Eco-anxiety cukup jadi bukti kalau krisis iklim hari ini bukan cuma berdampak terhadap lingkungan, ekonomi, politik, atau hal-hal lain yang sifatnya makro, tapi juga terhadap kesehatan mental kita semua. Kondisi ini memang tidak langsung menyebabkan kematian, tetapi ia perlahan-lahan menggerogoti harapan.
Dalam sebuah survei terhadap responden berusia 16-25 tahun, 59% responden merasa sangat cemas terhadap krisis iklim, dan lebih dari separuhnya merasakan sedih, tak berdaya, atau emosi negatif lainnya. Dalam jangka panjang, emosi-emosi negatif ini bisa memicu berbagai gangguan kesehatan, seperti panic attack, insomnia, penurunan sistem kekebalan tubuh, hingga depresi.
Gen-Z adalah generasi yang lebih rentan mengalami eco-anxiety, menurut sebuah studi. Gen-Z tumbuh dalam dunia yang terhubung secara digital. Mereka sangat cepat menyerap informasi tentang kebakaran hutan Amazon, suhu bumi yang terus meningkat, kenaikan permukaan laut, dan dampak krisis iklim lainnya.
Di sisi lain, teknologi digital jugalah yang membuat mereka cenderung terisolasi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tetapi, kondisi itu justru membuat sebagian Gen-Z sadar bahwa mereka harus memutus mata rantai keputusasaan akan masa depan. Dimulai dari eco-anxiety yang sama, mereka mulai menyebarkan awareness dan membangun salah satu gerakan kolektif terbesar abad ini.
Kolektivitas adalah Harapan
Pada 20 Agustus 2018. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun duduk di depan gedung parlemen Swedia. Ia membawa spanduk sederhana bertuliskan Skolstrejk for Klimatet Aksi Mogok Sekolah untuk Iklim. Tidak ada teman sekolah, tidak ada guru, tidak ada siapapun. Anak perempuan berbalut jas hujan warna kuning itu duduk sendirian itu bernama Greta Thunberg.
Kebakaran hutan dan gelombang panas di Eropa yang memecahkan rekor adalah alasan Greta melakukan aksi mogok sekolah kali pertama. Hanya butuh sehari bagi Greta untuk menarik perhatian dan simpati.
"Di mogok hari pertama, aku duduk sendirian dari jam 8.30 pagi sampai 3 sore-sepanjang jam sekolah. Dan di hari kedua, orang-orang mulai bergabung. Setelah itu, selalu ada orang baru yang bergabung," kata Greta, dikutip dari The Guardian.
Aksi mogok Greta bagai gelombang yang memunculkan keberanian. Anak-anak sekolah di berbagai belahan dunia mulai terinspirasi. Dari Jerman hingga Australia, dari Nigeria hingga Indonesia, anak-anak sekolah yang mayoritas adalah Gen-Z turun ke jalan dan mengambil alih ruang publik. Mereka menyebutnya Fridays for Future (FFF), sebuah gerakan mogok sekolah setiap Jumat untuk menuntut pemerintah dan politisi mencegah krisis iklim semakin parah. Pada September 2019, FFF mencapai puncaknya dengan lebih dari 4 juta peserta aksi dari seluruh dunia turun ke jalan.
Aksi mogok global ini membalikkan anggapan bahwa anak-anak tak punya suara dalam persoalan yang dianggap urusan orang dewasa. Lebih dari itu, sebagai mayoritas peserta aksi, Gen-Z juga membuka mata banyak orang bahwa krisis iklim tak bisa dilepaskan dengan isu sosial lain, salah satunya ketimpangan ekonomi.
 Greta Thurnberg/ Foto: Dave J Hogan/Getty Images/Dave J Hogan Greta Thurnberg/ Foto: Dave J Hogan/Getty Images/Dave J Hogan |
Konektivitas adalah Jembatan
Negara-negara miskin yang kontribusi emisinya kecil justru menanggung dampak terburuk dari krisis iklim. Bangladesh, misalnya, meskipun hanya menyumbang 0,3% emisi gas rumah kaca global namun berada di peringkat ke-9 negara yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim pada 2024. Bangladesh diperkirakan akan kehilangan 11% wilayah daratannya, mengakibatkan 18 juta orang harus kehilangan tempat tinggal pada 2050.
Kondisi Indonesia tidak jauh berbeda. Menurut Climate Central Indonesia, seperti dikutip The Jakarta Post, diperkirakan 23 juta penduduk Indonesia, terutama yang berada di wilayah pesisir, berisiko kehilangan tempat tinggal pada 2050 akibat naiknya permukaan air laut.
Ironisnya, mereka yang memiliki jejak karbon paling rendah dan menjaga stabilitas ekosistem seperti nelayan, petani, dan masyarakat adat adalah kelompok yang paling rentan dengan krisis iklim. Mereka harus berhadapan dengan ketidakpastian alam yang berdampak pada penghidupan sehari-hari.
Sebagai seorang aktivis iklim, Greta paham betul keterkaitan ini.
Pada 2021, ketika bergabung dengan demonstrasi masyarakat adat Sámi di Norwegia yang memprotes pengambilalihan lahan mereka untuk pembangunan turbin angin. Greta mengatakan, hak masyarakat adat dan hak asasi manusia harus berjalan beriringan dengan aksi iklim. Jika kita mengorbankan hak sebagian orang, itu bukanlah keadilan iklim.
Jadi, Eco-anxiety yang saya dan jutaan orang lain rasakan ternyata memiliki dimensi sosial yang kompleks. Namun, saya sadar bahwa di tengah krisis dan ketidakpastian akan selalu lahir harapan dari mereka yang memilih untuk saling mendengarkan dan menguatkan.
Apakah kamu merasakan hal yang sama?
Penulis: Arlandy Ghiffary
*Segala pandangan dan opini yang disampaikan dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi institusi atau pihak media online.*
(ktr/DIR)