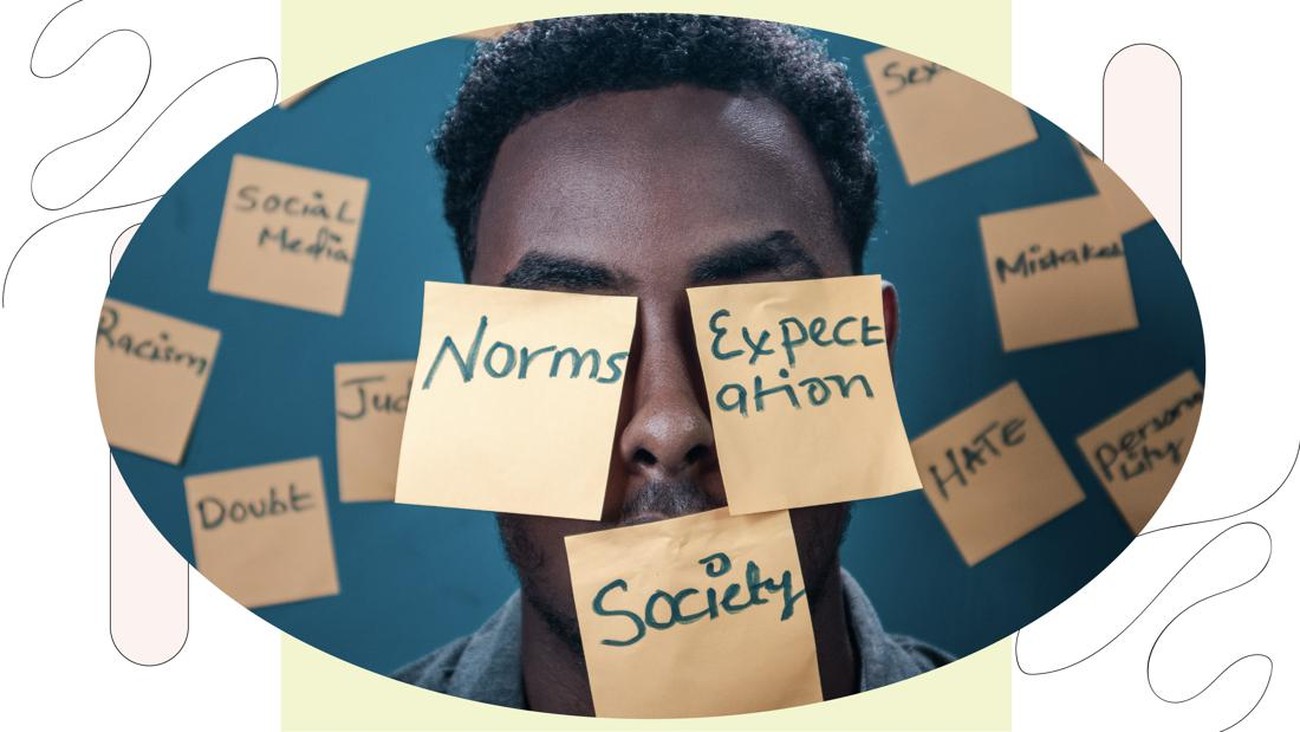Sanksi sosial adalah salah satu hukuman yang kerap diterima para pelanggar norma di masyarakat dan atau diterima oleh para pelaku tindak pidana. Di masyarakat modern, fenomena ini juga dikenal dengan "cancel culture", di mana hukuman berupa penolakan publik atau pemboikotan dijatuhkan kepada seseorang yang kebanyakan berasal dari kalangan figur publik, seperti selebritis atau tokoh politik. Sejauh ini, sudah banyak contoh kasus sanksi sosial atau cancel culture di masyarakat. Misalnya kasus penipuan binary option yang didalangi Indra Kenz, kasus kekerasan seksual yang problematis oleh Gofar Hilman dan Saiful Jamil, juga beberapa kasus lain yang serupa.
Meski penerapan cancel culture dirasa tepat untuk menindak para pelanggar norma, hal ini justru menimbulkan permasalahan baru. Yakni pemberian sanksi yang kelewat batas dan cenderung mengikis hak asasi si pelaku itu sendiri, seperti merusak nama baik, karir, hingga mata pencaharian mereka. Bahkan pada beberapa kasus di Korea Selatan, cancel culture justru berlaku lebih kejam dari pada sanksi pidana yang ada.
Hal ini menjadi penting untuk disoroti, mengingat sanksi sosial adalah suatu resolusi dari konflik dan bukan pencipta masalah baru. Di samping itu, tidak jelasnya batasan dari sanksi sosial itu sendiri malah mampu membuat masyarakat melanggar norma dan ketentuan hukum yang berlaku akibat penindakan yang berlebihan. Maka pertanyaan besarnya adalah, sebenarnya adakah batasan-batasan yang sesuai pada praktik pemberian sanksi sosial?
 Ilustrasi sanksi sosial/ Foto: Pixabay Ilustrasi sanksi sosial/ Foto: Pixabay |
Pemberian Sanksi yang Kelewat Batas
Berbeda dengan sanksi hukum yang diatur secara jelas oleh undang-undang dan ketentuan lainnya, sanksi sosial berjalan dengan sporadis di masyarakat karena memang kesepakatannya pun diatur secara tidak formal. Walaupun begitu, sanksi sosial tetap dirasa tepat dalam menindak pelanggar norma, karena masyarakat sebagai poros utama dalam kehidupan juga memiliki hak dalam mendefinisikan kehidupan sosial yang sama-sama mereka tinggali.
Namun masalahnya, dalam menindak pelaku yang dijatuhkan sanksi sosial, masyarakat terkadang kehilangan kendalinya dan seakan-akan berlaku sebagai hakim sosial yang pantas menghakimi kehidupan pelaku secara habis-habisan. Misalnya dalam beberapa kasus, pelanggar norma justru diserang hingga ke aspek paling privat dalam hidup yang seharusnya tidak disentuh oleh publik. Seperti halnya keluarga dekat atau kerabat dari pelaku yang turut diserang secara tidak menyenangkan, sebagai imbas dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
Lalu ada pula penindakan sanksi sosial yang sangat berlebihan, seperti dengan tetap menilai pelaku sebagai antagonis yang tidak akan pernah berubah, menutup segala lubang pencaharian sang pelaku atas nama kesalahannya di masa lampau, hingga diisolasi secara total dari masyarakat, sekalipun orang tersebut telah melakoni hukuman secara pidana yang pantas dan telah mencoba memperbaiki kesalahannya.
Hal-hal seperti itulah yang faktanya bergulir bebas di masyarakat ketika sedang memberi sanksi sosial terhadap seseorang. Lantas, fenomena ini menjadi suatu ironi, mengingat hukuman pidana saja memiliki tenggat waktu yang jelas, dan disertai dengan upaya merehabilitasi pelanggar hukum agar bisa kembali ke masyarakat secara baik dan bisa kembali mendapat kehidupan yang layak.
Nihilnya batasan dari cancel culture ini seringkali membuat masyarakat berlaku sewenang-wenang. Termasuk merasa lebih baik daripada pelaku, merasa memiliki kuasa untuk menghukumnya dengan berat, dan tidak mengindahkan hak asasi dari pelaku itu sendiri yang harusnya tetap dijaga dan dihormati.
 Permintaan maaf/ Foto: Pixabay Permintaan maaf/ Foto: Pixabay |
Bisakah Kita Bijak dalam Memberi Sanksi Sosial?
Menjatuhkan sanksi kepada seseorang bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharuskan berlaku objektif dalam menjalankan tugasnya. Tapi jika melihat sanksi sosial yang kendalinya dipegang masyarakat secara luas, subjektivitas dalam praktiknya akan terasa lebih dominan dan mungkin saja menghilangkan esensi dari sanksi itu sendiri yang bertujuan meresolusi konflik dan memberi efek jera, bukan malah berlaku over-judgmental.
Membincang soal sanksi sosial yang diatur tidak tertulis memang akan selalu rumit. Tetapi setidaknya, kita bisa mempelajarinya dari beberapa kasus yang pernah terjadi. Misalnya, menolak publik figur pelanggar norma untuk kembali mengisi platform media atau tampil di muka umum sebagai tokoh penting adalah hal yang cukup untuk dijatuhkan sebagai sanksi. Jadi, menyerang privasi para pelaku dan menutup semua lubang pencahariannya adalah hal yang tidak tepat dan malah membuat kita menjadi sosok yang jahat.
Selain itu, memutus akses hidup mantan pelaku yang telah melakoni hukuman secara formal juga tidak bisa kita lakukan. Sebab rasanya, hal ini akan berseberangan dengan undang-undang, di mana hak berkehidupan dari setiap warga negara telah diatur secara jelas oleh hukum. Kemudian, kita juga tidak bisa berbicara dengan tidak hormat apalagi melecehkan pelaku, sebab hal itu justru mendapuk kita sebagai pelanggar baru, yang bisa jadi lebih merugikan secara moral daripada pelaku itu sendiri.
Dalam memberi sanksi, kita juga perlu menjaga objektivitas secara terstruktur. Misalnya dengan menyamaratakan hukuman kepada siapa pun, sekalipun pelaku tersebut adalah mantan tokoh penting. Hal ini demi menghindari hukum pandang bulu yang seringkali tajam ke bawah dan malah tumpul ke atas. Lebih lanjut lagi, mungkin negara bisa membantu menciptakan hukum tentang penerapan tindak sanksi sosial, agar tiada perilaku kelewatan yang bisa saja dilakukan oleh masyarakat. Hal ini demi menjamin hak berkehidupan dari setiap warga negara, yang walaupun memiliki kesalahan, tetap patut memiliki kehidupan yang sebagaimana mestinya, meski tidak lagi sama dengan kehidupannya di masa lalu yakni sebelum pelaku melanggar norma atau hukum yang berlaku.
(RIA/HAL)