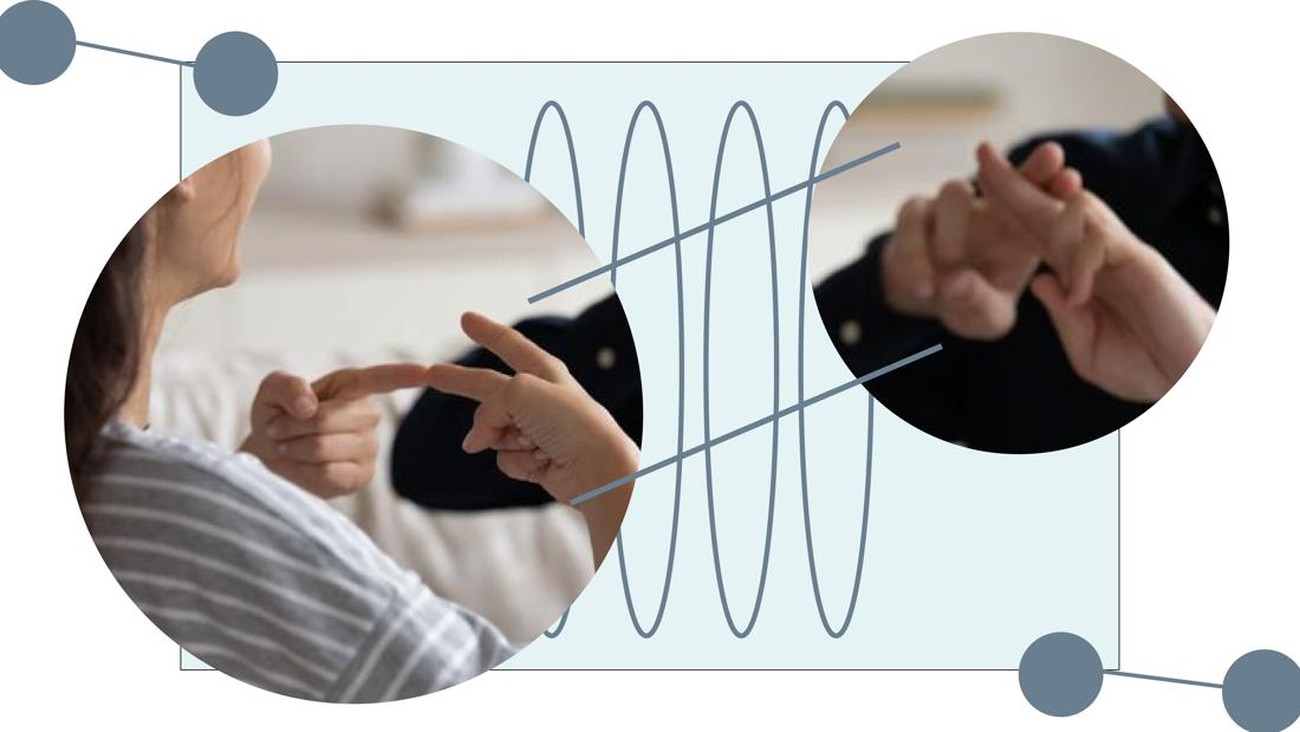Bagja Prawira divonis tuli oleh dokter sejak dirinya berusia 3 tahun. Saat itu telinga kirinya tak bisa digunakan untuk mendengar, sedangkan telinga kanannya masih mampu menangkap suara meski di bawah kemampuan orang-orang pada umumnya. Akibat kondisinya tersebut, Bagja harus menggunakan alat bantu dengar.
Namun seiring waktu, Bagja mengasah kemampuannya untuk bisa beradaptasi dan membaur dengan lingkungan sekitar, bahkan juga akhirnya mampu berkomunikasi secara verbal. Hingga akhirnya pada tahun 2016, dunia Bagja runtuh seketika saat pendengarannya hilang 100 persen. Berita buruk yang datang untuk kedua kalinya itu sempat membuat ia kehilangan harapan.
"Saya butuh waktu 3 bulan untuk mengurungkan diri di rumah karena merasa takut untuk bertemu dengan orang lain. Saya khawatir ketika bertemu dengan orang lain saya tidak bisa memahami apa yang mereka ucapkan," ungkapnya kepada CXO Media.
Dengan bantuan orang terdekat, Bagja akhirnya mampu berdamai dengan kondisi yang ia alami dan tidak menganggapnya sebagai hambatan. Tak berhenti di situ, Bagja juga aktif mengadvokasi aksesibilitas bagi teman Tuli, salah satunya melalui platform Silang.id yang ia bantu dirikan.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2019, ada sekitar 18,9 juta orang di Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas rungu. Namun dari 18 juta orang tersebut, tak semuanya bisa beraktivitas dan bekerja seperti Bagja. Bukan karena mereka tak mampu, tapi karena kita belum bisa mewujudkan masyarakat yang inklusif.
Bagi Tuli, kondisi yang mereka alami bukanlah hambatan. Hambatan yang mereka alami justru datang dari minimnya ketersediaan akses untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan publik. Selain itu, mereka masih harus menghadapi berbagai diskriminasi dan stereotip yang terlanjur mengakar di masyarakat.
Tuli Bukan Berarti Bisu
Tahun lalu, publik sempat dihebohkan dengan cerita seorang calon mitra perusahaan transportasi daring yang menerima perlakuan diskriminatif saat ia melamar pekerjaan. Meski sudah menunjukkan undangan wawancara dan menyatakan kalau dirinya adalah seorang Tuli, tapi ia justru diusir oleh petugas keamanan. Ia bahkan sempat diminta untuk membaca dengan jelas dan keras untuk diuji apakah benar-benar mengalami gangguan pendengaran. Peristiwa ini menggambarkan realita yang dialami oleh Tuli; mereka rentan didiskriminasi dan kerap diasingkan dari kehidupan publik.
Masih ada banyak Tuli yang tak familiar dengan dunia kerja, dan sebaliknya masih banyak perusahaan yang belum inklusif. Hal ini diakibatkan oleh kuatnya stereotip terhadap Tuli, mereka dianggap tak bisa berkomunikasi dan oleh karenanya tak bisa berkontribusi.
"Stereotip yang paling sering ditemui di kalangan komunitas Tuli itu adalah banyak orang menganggap Tuli sama dengan bisu. Padahal tidak semua teman Tuli itu bisu, karena Tuli tidak ada kaitannya dengan tidak bisa berbicara," ungkap Bagja.
Stereotip tersebut kerap muncul ketika teman Tuli melamar pekerjaan. Padahal, teman Tuli punya cara lain untuk berkomunikasi, misalnya dengan menulis atau dengan bantuan Juru Bahasa Isyarat. Menyamakan Tuli dengan bisu sama saja dengan menganggap mereka tak memiliki suara, padahal Tuli mampu bersuara layaknya orang pada umumnya. Hanya saja, aksesnya yang seringkali tidak tersedia.
Bagja memberi contoh, di Amerika Serikat sudah ada banyak institusi pendidikan yang menyediakan akses Juru Bahasa Isyarat. Sehingga, baik orang Tuli maupun orang Dengar bisa ikut dalam satu kelas yang sama tanpa harus dibeda-bedakan. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia yang masih belum menyediakan akses bagi teman Tuli. Jangankan menyediakan akses, masyarakat saja masih banyak yang merasa asing dengan komunitas Tuli. Jadi meski jumlah Tuli mencapai 18 juta, tapi nyatanya kita masih belum hidup berdampingan.
Menjadi Ally Bagi Teman Tuli
Kuatnya stereotip yang mengakar di dalam masyarakat tak bisa dilepaskan dari rasa asing yang pada akhirnya menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpedulian. Tak banyak masyarakat yang mau mempelajari cara hidup teman Tuli, termasuk bagaimana mereka berkomunikasi. Sehingga pada akhirnya, gap yang telah tercipta itu menciptakan jarak dan sekat yang membatasi sejauh apa inklusivitas bisa diwujudkan dalam masyarakat Indonesia.
Untuk mewujudkan inklusivitas, hak-hak Tuli harus bisa dipenuhi. Hak-hak teman Tuli sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Beberapa hak yang diatur dalam UU tersebut di antaranya adalah hak untuk bebas dari stigma; hak untuk bekerja; hak untuk bisa hidup mandiri di tengah masyarakat; dan juga hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi.
Meski sudah diatur oleh undang-undang, tapi nyatanya pemenuhan hak teman Tuli masih belum sepenuhnya terwujud. Salah satu contohnya, banyak teman Tuli yang kesulitan mendapatkan informasi karena tak semua konten audio-visual dilengkapi dengan closed caption atau Juru Bahasa Isyarat. Padahal, dua hal sederhana ini sangat dibutuhkan untuk aksesibilitas teman Tuli.
Selain melalui regulasi, hak-hak teman Tuli juga lebih bisa terpenuhi apabila ada banyak masyarakat yang mau menjadi ally atau teman dengar. Menurut Bagja, untuk menjadi ally bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, salah satunya yaitu dengan menghilangkan segala asumsi mengenai Tuli.
Kenali teman Tuli dengan berinteraksi secara langsung dengan mereka, agar stereotip dan stigma yang sudah melekat bisa dihapuskan. Cara berikutnya adalah dengan belajar bahasa isyarat. Sebagian besar teman Tuli menggunakan BISINDO untuk berkomunikasi, kalian bisa menemukan berbagai rekomendasi tempat belajar yang menyediakan kelas bahasa isyarat. Kemudian kalau sudah fasih menggunakan bahasa isyarat, kalian bisa memperjuangkan hak-hak Tuli dimulai dari lingkungan sekitar.
(ANL/DIR)